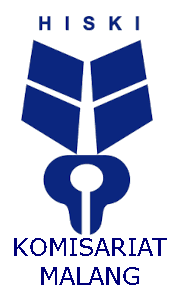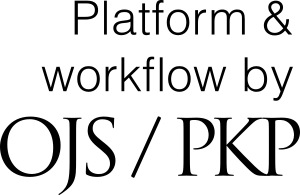Puji syukur, Jurnal Pembelajaran Sastra Edisi 6 Nomor 1 tahun 2024 telah sampai ke hadapan para pembaca. Edisi ini menampilkan lima artikel dari empat institusi yang berbeda: tiga dari institusi dalam negeri (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Negeri Malang, dan SMA N 10 Malang) serta satu artikel dari Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages, China.
Kelima artikel yang tersaji dalam edisi kali ini menampilkan tema yang menunjukkan keterkaitan erat antara sastra dan pengalaman dunia nyata melalui berbagai kajian akademis. Dalam puisi Edgar Allan Poe yang berjudul "Alone," analisis biografis dan simbolistik mengungkap bagaimana Poe menggunakan narasi "Aku" untuk mencerminkan masa kecilnya yang penuh tantangan. Puisi ini terbagi dalam tiga fase: tahun-tahun awal Poe dengan ibu kandungnya, kehidupannya bersama keluarga Allan, dan dampak emosional kehilangan ibu angkatnya. Melalui simbol-simbol seperti badai, sinar matahari, dan setan, Poe menggambarkan emosinya yang penuh gejolak dan pengalamannya. Refleksi pribadi ini menunjukkan bagaimana sastra sering kali mencerminkan dunia batin penciptanya, menggunakan representasi simbolik untuk mengomunikasikan makna yang lebih dalam tentang kehidupan, perjuangan, dan kehilangan.
Serupa dengan bagaimana pengalaman hidup Poe memengaruhi karya sastranya, novel "The Wall" karya John Lanchester mencerminkan kekhawatiran global kontemporer tentang isu-isu lingkungan. Dengan menggunakan pendekatan ekokritik, studi tentang novel ini menunjukkan bagaimana narasi sastra dapat menggambarkan dampak perubahan iklim, polusi, dan krisis lingkungan lainnya. Novel ini menekankan pentingnya kesadaran dan tindakan terhadap degradasi lingkungan, menjadikan sastra sebagai alat yang kuat untuk advokasi lingkungan. Karya Poe dan Lanchester sama-sama menunjukkan bagaimana sastra dapat menjadi media untuk membahas isu-isu pribadi dan global, mengaitkan narasi individu dengan kepedulian masyarakat yang lebih luas.
Menerjemahkan karya sastra ke dalam berbagai bahasa dapat memperkuat tema dan pesan ini, seperti yang ditunjukkan dalam studi tentang terjemahan "Qasidah Burdah" oleh Ibnu Abroh. Penelitian ini berfokus pada keakuratan terjemahan dan bagaimana berbagai teknik, seperti terjemahan harfiah dan idiomatik, memengaruhi makna yang disampaikan. Studi ini menemukan bahwa 84,66% terjemahan tergolong akurat, tetapi juga menyoroti tantangan dalam mempertahankan esensi karya asli dalam bahasa yang berbeda. Proses terjemahan tidak hanya melibatkan keakuratan linguistik, tetapi juga sensitivitas budaya untuk mempertahankan makna penting karya tersebut, mirip dengan bagaimana narasi Poe dan Lanchester memerlukan interpretasi yang cermat agar dapat dipahami dan dihargai sepenuhnya.
Eksplorasi tentang bagaimana karya sastra dianalisis juga diperluas ke esai-esai sosiologis, seperti yang disoroti dalam analisis esai-esai sosiologis Arief Budiman. Berbeda dengan kritikus yang bertujuan mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan suatu karya sastra, esais berinteraksi dengan teks sebagai pemikir, menawarkan refleksi dan interpretasi baru. Hal ini ditunjukkan dalam esai kritis Ignas Kleden, yang mengkaji simbolisme tubuh dalam puisi-puisi Joko Pinurbo. Dengan beralih dari simbolisme tradisional yang berasal dari alam ke simbolisme yang berpusat pada tubuh, esai ini menyajikan perspektif baru tentang bagaimana sastra dapat mencerminkan dimensi masyarakat dan budaya. Analisis mendalam semacam ini menekankan hubungan dinamis antara sastra dan refleksi sosial, menunjukkan bagaimana berbagai perspektif dapat memperkaya pemahaman kita tentang teks.
Akhirnya, penerapan praktis dari analisis sastra dan bercerita terlihat dalam studi kasus Departemen Bahasa Indonesia di Universitas Bahasa Asing Zhejiang Yuexiu. Di sini, bercerita digunakan sebagai alat instruksional untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan siswa dan kesadaran budaya. Studi ini menekankan pentingnya desain instruksional dalam melibatkan siswa secara efektif, menunjukkan bahwa mengintegrasikan cerita dengan tujuan pembelajaran dapat mendorong perolehan bahasa yang lebih baik dan pemahaman budaya. Temuan ini sejalan dengan tema yang lebih luas bahwa sastra, baik dianalisis untuk isinya yang simbolik, biografis, atau sosiokultural, dapat menjadi media yang kuat untuk pendidikan dan refleksi tentang isu-isu pribadi, sosial, dan lingkungan.
Tabik.